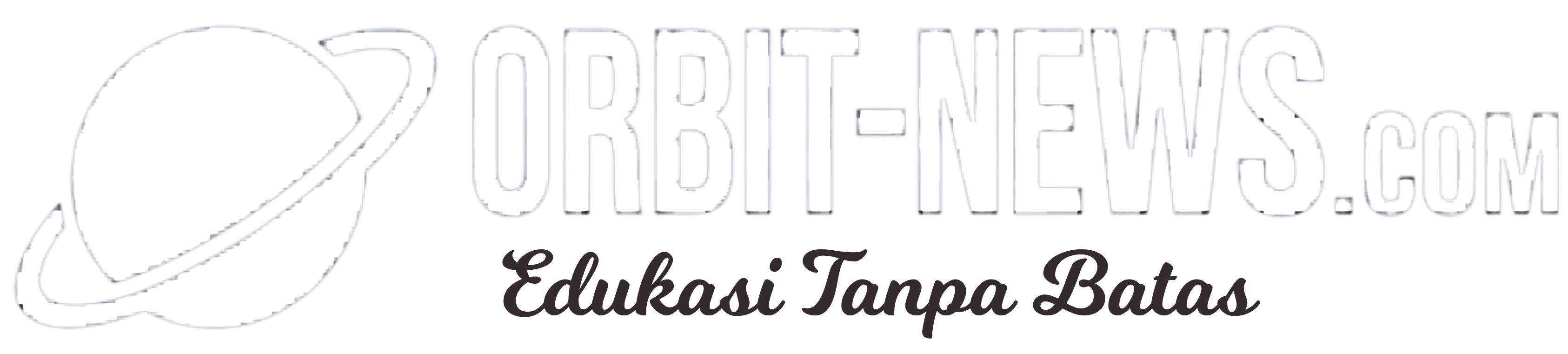ORBIT-NEWS.COM,
PURWOKERTO - Gunung Slamet, atap Jawa Tengah yang selama ini berdiri gagah
menaungi Kabupaten Banyumas, sedang tidak baik-baik saja. Di balik kabut tipis
dan hijau hutannya yang menyejukkan mata wisatawan, tersimpan narasi kelam
tentang perebutan ruang hidup yang kian hari kian meruncing. Jika kita
mendekatkan telinga ke tanah di lereng selatannya, yang terdengar bukan lagi
sekadar gemericik air jernih, melainkan deru mesin berat dan keluh kesah warga
yang terpinggirkan. Apa yang terjadi di Banyumas belakangan ini bukanlah
peristiwa sporadis yang berdiri sendiri, melainkan cermin retak dari wajah
pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang carut-marut.
Realitas pahit ini terekam jelas dalam ingatan kolektif warga. Kita belum lupa bagaimana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang nyata. Sebagaimana dicatat dalam laporan Mongabay (2025), pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Slamet telah memicu dampak domino yang mengerikan. Sungai Prukut yang dulu sebening kaca, berubah keruh kecokelatan, membawa lumpur sisa aktivitas pembukaan lahan, mematikan geliat ekonomi perikanan warga, dan merusak sumber air bersih yang menjadi urat nadi kehidupan desa-desa di bawahnya. Proyek yang digadang-gadang sebagai energi hijau justru hadir dengan wajah yang merusak keseimbangan alam yang telah terjaga ratusan tahun.
Baca juga: Kritik, Komedi, dan Bullying: Pelajaran Kitab Akhlak Pesantren dari Kontroversi Pandji–Gibran
Belum kering luka akibat proyek panas bumi, ancaman lain muncul dari aktivitas pertambangan galian C. Di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, keresahan warga memuncak hingga melahirkan tuntutan tegas: penutupan permanen aktivitas tambang. Seperti diberitakan beberapa media, warga tidak lagi bisa mentoleransi risiko kerusakan lingkungan yang mengancam pasokan air bersih mereka. Sementara itu, sedikit bergeser ke timur, di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, aktivitas pertambangan serupa meninggalkan jejak kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang masif. Debu beterbangan menyesakkan dada, jalan-jalan desa hancur dilindas truk pengangkut material, dan ancaman longsor menghantui setiap kali hujan deras turun.
Pola yang terjadi di Lereng Slamet, mulai dari Baturraden, Baseh, hingga Gandatapa, adalah mikrokosmos dari tragedi ekologis nasional. Ia memiliki tarikan napas yang sama dengan konflik di Wadas, Purworejo, di mana warga harus berhadapan dengan represifitas aparat demi mempertahankan tanah dari tambang andesit. Ia senada dengan jeritan petani Pegunungan Kendeng yang menolak pabrik semen demi menjaga cekungan air tanah, atau masyarakat adat di luar Jawa yang hutan adatnya digilas demi sawit dan nikel. Untuk memahami benang kusut ini, kita tidak bisa sekadar melihat permukaan. Diperlukan sebuah pisau bedah analisis sosial yang tajam untuk memetakan siapa yang bermain dan di mana kita harus berpihak.
Baca juga: Tabayun Lirboyo: Ketika Kiai Memilih Islah Mengalahkan Ego
Langkah pertama dalam anatomi konflik ini adalah memetakan aktor dan relasi kuasa yang bekerja di dalamnya. Dalam kasus PLTPB Baturraden maupun tambang di Baseh dan Gandatapa, terlihat jelas adanya relasi yang asimetris. Di satu sisi, terdapat aliansi aktor yang diuntungkan (the winners), yakni korporasi atau investor yang memegang izin konsesi dan negara (pemerintah pusat hingga daerah) yang mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau realisasi investasi. Bagi kelompok ini, alam Gunung Slamet hanyalah komoditas; sekumpulan angka dalam neraca ekonomi yang harus diekstraksi demi pertumbuhan. Mereka memiliki segalanya: legalitas hukum, modal finansial, dan seringkali dukungan aparat keamanan untuk mengamankan ‘objek vital’ investasi mereka.
Di sisi berseberangan, berdiri para aktor yang dirugikan (the losers), masyarakat desa, petani, perempuan, dan tentu saja, alam itu sendiri. Bagi warga Baseh dan Gandatapa, gunung dan sungai bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup (lebensraum) yang menopang sejarah, budaya, dan kelangsungan hidup antargenerasi. Ketika air menjadi keruh atau jalan menjadi rusak, merekalah yang menanggung biaya eksternalitas negatif tersebut secara langsung. Relasi ini memperlihatkan ketidakadilan struktural yang telanjang: keuntungan diprivatisasi oleh segelintir elite, sementara kerugian disosialisasi dan ditanggung oleh rakyat banyak.
Baca juga: Majelis Taklim untuk Gen Masa Depan
Melihat ketimpangan yang begitu nyata, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita harus bersikap? Di sinilah kerangka paradigmatik yang ditawarkan oleh Henry Giroux dan Stanley Aronowitz dalam karya seminal mereka tahun 1985, Education Under Siege, menjadi sangat relevan untuk dipinjam. Meski awalnya digunakan dalam konteks pendidikan, trikotomi paradigma Giroux dan Aronowitz—Konservatif, Liberal/Moderat, dan Kritis—sangat presisi untuk membedah posisi ideologis kita dalam memandang konflik sumber daya alam.
Jika kita menggunakan paradigma konservatif, kita akan memandang konflik di Banyumas sebagai konsekuensi logis dari 'takdir' pembangunan. Penganut paradigma ini cenderung menyalahkan masyarakat (blaming the victim). Mereka akan berkata bahwa warga desa yang menolak tambang adalah kelompok yang anti-kemajuan, tidak paham hukum, atau sekadar penghambat investasi nasional. Dalam kacamata ini, status quo harus dipertahankan, dan jika perlu, ketertiban sosial ditegakkan dengan cara-cara represif demi menjaga stabilitas ekonomi. Pandangan ini menafikan fakta bahwa kemiskinan warga seringkali justru disebabkan oleh perampasan sumber daya alam mereka oleh kekuatan luar. Bergeser sedikit, kita menemukan paradigma liberal atau moderat. Ini adalah posisi yang paling sering diambil oleh birokrat, sebagian akademisi, dan politisi yang ingin terlihat ‘bijak’. Penganut paradigma moderat mengakui adanya kerusakan lingkungan di PLTPB Baturraden atau Gandatapa, namun mereka percaya bahwa solusinya ada pada perbaikan prosedur, bukan perombakan sistem. Mantra mereka adalah ‘Pertambangan Berkelanjutan’, ‘Green Mining’, atau penguatan Analisis.
Baca juga: Pendidikan dalam Spirit Kearifan Lokal Banokeling
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka beranggapan bahwa tambang dan warga bisa hidup berdampingan asalkan ganti ruginya layak. Paradigma ini seringkali menjebak, karena seolah-olah memberikan solusi, padahal hanya memoles permukaan tanpa menyentuh akar masalah: bahwa daya dukung Gunung Slamet sudah tidak mampu menahan beban eksploitasi.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai kerusakan ini adalah dengan mengadopsi paradigma kritis, sebagaimana ditawarkan Giroux dan Aronowitz (1985). Paradigma kritis tidak terjebak pada persoalan teknis prosedural seperti AMDAL atau besaran ganti rugi. Lebih jauh, paradigma ini menggugat struktur kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi itu terjadi. Dengan kacamata kritis, kita melihat bahwa kasus Baseh dan Gandatapa bukan sekadar ‘kecelakaan’ atau ‘kelalaian oknum’, melainkan konsekuensi inheren dari sistem ekonomi politik yang menghamba pada akumulasi modal.
Dalam paradigma kritis, keberpihakan menjadi kunci. Sikap netral dalam situasi ketidakadilan, menurut Paulo Freire yang juga menginspirasi Giroux, sama saja dengan memihak pada penindas. Maka, keberpihakan kita harus jelas: berpihak pada mereka yang dirugikan. Berpihak pada warga Baseh, Gandatapa dan warga terdampak PLTPB.
Pilihan paradigma ini memengaruhi tindakan praksis kita. Jika kita kritis, kita tidak akan lagi mendorong 'mediasi', yang seringkali timpang, melainkan mendorong ‘advokasi’. Kita tidak lagi berbicara soal ‘ganti rugi’, melainkan ‘pemulihan hak’. Tindakan nyata yang lahir dari kesadaran kritis adalah membangun solidaritas lintas batas. Gerakan tolak tambang di Banyumas harus dilihat sebagai satu tarikan napas dengan gerakan lingkungan global. Selain itu, upaya hukum (litigasi) harus dibarengi dengan pendidikan politik rakyat dan kampanye publik yang masif.
Sebagai penutup, apa yang terjadi di Banyumas adalah alarm keras bagi kita semua. Kerusakan akibat PLTPB Baturraden dan tambang galian C di sekitarnya adalah bukti bahwa paradigma pembangunan kita telah melenceng jauh dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan ruang hidup rakyat atas nama investasi. Sudah saatnya kita menanggalkan kacamata konservatif yang menyalahkan rakyat, membuang ilusi moderat yang hanya menawarkan ganti rugi semu, dan mulai berani mengambil sikap kritis yang radikal. Sebab, apabila Gunung Slamet ‘batuk’, karena terus digerogoti kakinya, bukan hanya investor yang akan lari menyelamatkan modalnya, tetapi rakyat kecillah yang akan terkubur bersama mimpi-mimpi mereka yang dirampas. Menyelamatkan Baseh dan Gandatapa adalah upaya menyelamatkan masa depan kita sendiri.
Penulis adalah Peneliti
Senior Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto dan UIN Prof Saifuddin
Zuhri Purwokerto.
Belum ada komentar.
Orbit-News.com membuka ruang bagi suara publik melalui rubrik Orbit Vox. Di sini, setiap pembaca dapat menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan, maupun laporan terkait berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Kami percaya, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menghadirkan informasi yang lebih jernih, berimbang, dan bermanfaat bagi semua.