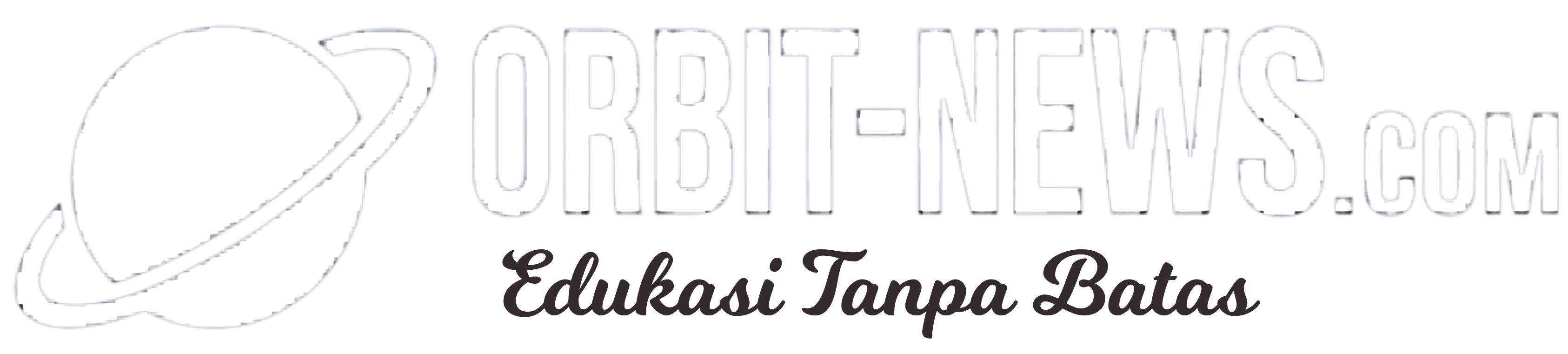ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO - Beberapa hari terakhir ruang publik kita gaduh. Bukan karena perang kebijakan, bukan pula karena debat konsep ekonomi, melainkan karena sepotong materi komedi.
Komika Pandji Pragiwaksono lewat special show Mens Rea yang tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025, menuai pro-kontra dan bahkan pelaporan polisi akibat materi yang dianggap menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk lelucon yang dituduh mengandung body shaming.
Ada yang membela Pandji atas nama kebebasan berekspresi. Ada yang mengecamnya sebagai penghinaan terhadap simbol negara. Ada pula yang menilai pelaporan ini berlebihan dan berpotensi mengancam iklim kritik dan satire.
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD bahkan berpendapat materi tersebut tidak serta-merta memenuhi unsur pidana. Namun, dalam kegaduhan itu ada satu isu yang sering luput: bukan soal siapa yang lebih benar, melainkan kebiasaan sosial apa yang sedang kita normalisasi. Sebab yang paling berbahaya dari kontroversi semacam ini adalah ketika publik lupa membedakan: kritik dan bullying. Kritik adalah kerja intelektual untuk menguji kebijakan dan perilaku publik; bullying adalah kerja psikologis untuk merobohkan martabat pribadi sering kali lewat ejekan fisik dan penghinaan karakter.
Tulisan ini tidak hendak menjadi pembela Pandji maupun Gibran. Pejabat publik boleh dikritik, bahkan wajib dikritik. Komedi satire juga bagian sah dari demokrasi. Tetapi ketika kritik atau komedi mulai menjadikan tubuh seseorang sebagai bahan olok-olok, mata, wajah, postur, kondisi biologis yang muncul bukan lagi kritik, melainkan perundungan yang diberi baju tawa. Dan di titik inilah, khazanah pesantren sesungguhnya punya sumbangan penting: kitab-kitab akhlak klasik telah sejak lama menjadi kurikulum anti-bullying, meski tanpa menyebut kata “bullying”.
Kezaliman Akhlak
Dalam tradisi pesantren, perilaku merendahkan orang lain masuk wilayah su’ul khuluq (akhlak tercela) dan zulm (kezaliman). Yang dipersoalkan bukan hanya “mengolok-olok”, melainkan melukai kehormatan manusia. Kalau istilah modern menyebutnya body shaming, kitab-kitab akhlak menyebutnya lebih tajam: menghina, menyakiti hati, merusak persaudaraan, dan membuka pintu hasad (dengki). Dalam bahasa sederhana: orang boleh kalah argumentasi, tapi jangan sampai kalah adab.
Maka body shaming bukan urusan sepele. Ia melahirkan budaya yang berbeda fisik dianggap pantas ditertawakan, yang lemah dianggap bahan hiburan, yang tidak sesuai standar dianggap objek celaan. Dalam jangka panjang, budaya ini berakhir pada generasi yang menganggap lumrah mempermalukan orang, asal penontonnya ramai.
Di sinilah pesantren menawarkan cara berpikir berbeda. Kitab-kitab seperti Ta’līm al-Muta’allim, Adāb al-‘Ālim wa al-Muta’allim, Wasāyā al-Ābā’ lil Abnā’, Akhlāq al-Banīn, dan Akhlāq al-Banāt membangun pagar moral agar ruang pendidikan tidak berubah menjadi panggung penghinaan.
Ta’līm al-Muta’allim: Ejekan mematikan berkah ilmu
Kitab Ta’līm al-Muta’allim mengajarkan satu prinsip mendasar: ilmu bukan hanya informasi, melainkan cahaya yang dititipkan kepada hati yang beradab. Karena itu, penyakit yang menghalangi ilmu bukan hanya malas, tetapi juga sombong dan kotor lisan. Bullying hampir selalu berangkat dari rasa superior: senior atas junior, kuat atas lemah, “yang dianggap sempurna” atas yang berbeda. Dalam istilah kitab, ini bernama kibr (kesombongan). Maka akar perundungan bukan humor, melainkan ego yang ingin menang dengan cara merendahkan.
Di pesantren, orang yang mencela temannya dipandang bukan lebih hebat, tetapi lebih miskin adab. Kitab ini seolah berkata: “Boleh pandai, boleh lucu, boleh tajam mengkritik. Tapi kalau tajamnya melukai kehormatan manusia, ilmu itu kehilangan berkah.” Adāb al-‘Ālim wa al-Muta’allim: Pendidikan harus melindungi martabat, bukan menertawakannya KH. Hasyim Asy’ari dalam Adāb al-‘Ālim wa al-Muta’allim menempatkan pendidikan sebagai ekosistem akhlak. Guru bukan sekadar pengajar materi, melainkan penjaga adab dan marwah murid.
Kitab ini sangat relevan karena bullying hari ini tidak hanya terjadi antarsiswa, tetapi juga bisa lahir dari budaya lembaga, mempermalukan, memberi julukan, menjadikan kekurangan orang sebagai tontonan, atau menertibkan dengan cara yang merendahkan.
Maka pesan kuncinya jelas, tegas itu boleh, menghina itu haram. Kitab membedakan disiplin yang mendidik (ta’dīb) dari kekerasan yang menyakitkan (ta’dzīb). Pendidikan yang benar membentuk karakter tanpa merobek harga diri. Jika prinsip ini dibawa ke ruang publik, maka batas etiknya terang: boleh mengoreksi pejabat, boleh menyindir kebijakan, bahkan boleh menggugat logika kekuasaan tetapi jangan membangun kelucuan dari “kelemahan fisik” yang bukan pilihan manusia.
Wasāyā al-Ābā’ lil Abnā’: Kekuatan sejati adalah menahan diri
Wasāyā al-Ābā’ lil Abnā’ berisi nasihat pembentukan jiwa. Ia menanamkan bahwa manusia mulia bukan yang pandai menang debat, tapi yang mampu menang melawan hawa nafsu. Dalam dunia komedi, godaannya adalah mencari tawa tercepat. Dalam dunia politik, godaannya adalah menyerang lawan dengan cara termudah. Keduanya bisa tergelincir ke satu titik: menertawakan manusia, bukan gagasannya.
Kitab ini mendidik bahwa muru’ah (kehormatan diri) tampak dari kemampuan menahan lisan. Orang yang mampu mengendalikan kata-kata jauh lebih kuat daripada yang mampu membuat panggung gemuruh dengan cara merendahkan.
Akhlāq al-Banīn dan Akhlāq al-Banāt: Bullying sering bermula dari lisan
Dua kitab akhlak praktis ini sebenarnya merupakan modul anti-bullying yang sangat konkret. Akhlāq al-Banīn membimbing anak laki-laki agar menjadi kuat tanpa menindas. Akhlāq al-Banāt mendidik anak perempuan menjaga lisan dari gosip, sindiran, dan pola mengucilkan.
Keduanya menunjukkan: bullying paling sering terjadi bukan lewat pukulan, tetapi lewat kata-kata. Julukan buruk, sindiran, lelucon fisik, dan body shaming adalah pintu awal luka batin yang panjang. Jika sekolah dan pesantren menerapkan disiplin lisan sebagaimana kitab-kitab ini, maka budaya perundungan akan runtuh dari akar, bukan sekadar ditambal dengan sanksi administratif.
Kontroversi Pandji–Gibran pada akhirnya akan menjadi arsip waktu. Tetapi ada yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memahami batas etis dalam berucap. Jika publik menganggap body shaming sebagai “bagian wajar dari kritik” atau “sekadar bercanda”, maka generasi muda belajar satu hal buruk: mengejek fisik itu boleh asal lucu, merendahkan martabat itu sah asal ramai. Kitab klasik pesantren mengajarkan kebalikan dari itu: kritik adalah kerja akal; penghinaan adalah penyakit hati.
Dari pesantren, kita mendapat rumus sederhana sekaligus tegas:
1. Kritiklah kebijakan, bukan tubuh manusia.
2. Sindirlah perilaku, bukan fisik yang tak dipilih seseorang.
3. Tertawalah bersama, bukan menertawakan yang dijadikan sasaran.
Demokrasi butuh kritik, komedi butuh kebebasan. Tetapi bangsa ini juga butuh adab. Sebab tanpa adab, kritik berubah menjadi kekerasan verbal; komedi berubah menjadi panggung perundungan; dan masyarakat berubah menjadi ruang yang dingin bagi yang berbeda. Di tengah hiruk-pikuk kebebasan, pesantren mengingatkan kita bahwa kemerdekaan lisan harus dipandu kemuliaan akhlak. Jika tidak, kita bukan sedang membangun bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang ramai namun gemar meruntuhkan martabat sesamanya.
Penulis adalah Guru
Besar FUAH UIN Saizu Purwokerto